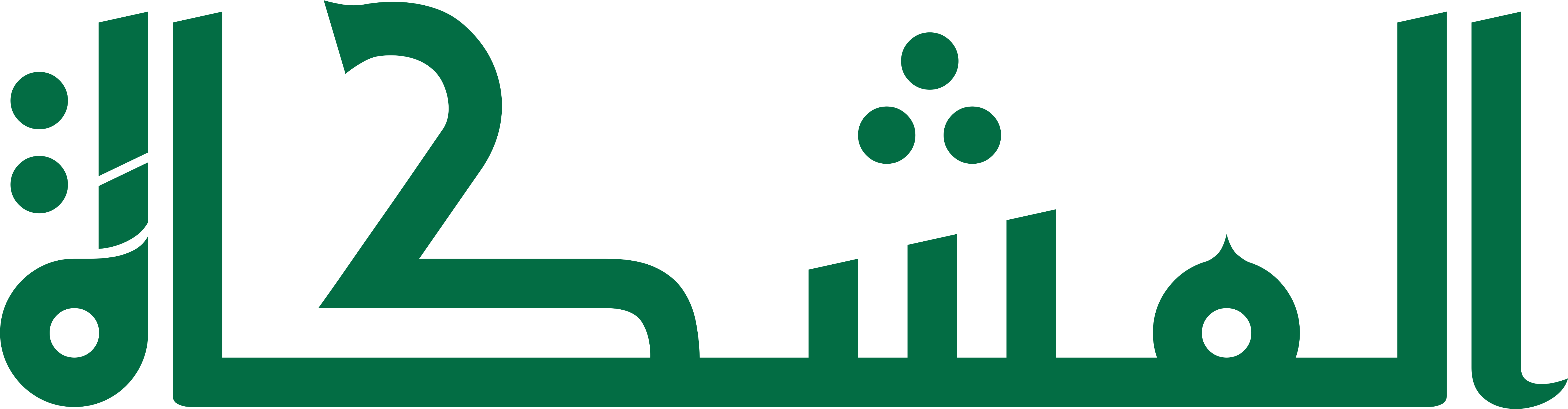Kebebasan ala lembah suara
Keadaan hening untuk beberapa waktu. Langit di atas mata air tampak semakin indah, berpadu dengan hembusan angin gunung yang lembut. Si Buta dan Si Buntung larut dalam diamnya masing-masing, seolah keduanya sedang menapaki kembali perjalanan yang telah mereka lalui.
Si Buntung perlahan membuka lipatan peta kecil yang sejak awal perjalanan tak pernah lepas dari genggamannya peta yang kini tampak rusuh, penuh coretan, dan warnanya mulai memudar.
“Setelah Desa Batu, lurus, lalu belok kiri, dan masuk ke lembah,” gumamnya pelan, seperti mengulang sesuatu yang sudah lama berlalu.
“Lembah yang ramai itu buntung?” tanya Si Buta, mencoba memastikan ingatannya.
Si Buntung tersenyum samar.
“Ya, lembah itu,” jawabnya pendek.
Keduanya terdiam sejenak. Angin berhembus membawa ingatan itu kembali, samar tapi hidup:
“Di lembah itu ramai sekali ya, Buntung. Pasti di sana banyak orang?” tanya Si Buta sambil menajamkan pendengarannya.
“Justru sepi, Buta,” jawab Buntung datar.
“Lho bagaimana mungkin sepi, telingaku mendengar sendiri semua suara-suara itu buntung, meskipun aku tidak bisa melihat, tapi aku masih bisa mendengar, ingat itu.”
Buntung menarik napas.
“Tadi saat kita mulai turun buta, aku bisa melihat penduduk di sana buta. Mereka tinggal di goa-goa. Mereka saling berteriak dari dalam sana.
Tapi apakah kau tau buta, anehnya, meski mereka saling berteriak tak satu pun teriakan itu saling menjawab.” Sambung si buntung
“Ah, pantas saja aku tak bisa memahami apa yang tengah mereka bicarakan,” sahut Buta. “Mereka sudah seperti lomba burung perkutut di lapangan desa itu ya buntung, semua hanya sibuk berkicau tapi tak ada yang memahaminya, hahaha.”
“Ngawur kamu, Buta,” ujar Buntung sambil tertawa kecil.
Si buntung lalu menunduk menatap sumber mata air di hadapannya melihat bagaimana air mengalir dan ikan-ikan tampak hidup bahagia karena hidupnya cukup dengan blubub-blubub, makan kemudian mati.
Si Buta memecah diam, “Apakah kau tahu, Buntung, lembah tadi sangatlah berbeda dari Desa Batu?”
“Apa maksudmu, Buta?”
“Iya buntung, coba kau ingat-ingat, tadi di desa Batu. Semua orang di sana diam. Tidak ada yang berani bicara, mereka hanya tunduk pada satu suara, suara kepala adat. Tapi di lembah itu, justru semua orang berbicara. Bukankah itu bagus, Buntung? Dengan begitu mereka jadi bebas untuk berekspresi dan menentukan diri sendiri apa yang akan mereka lakukan tidak seperti desa batu sebelumnya.”
Buntung tersenyum tipis, kemudian menyanggah.
“Apakah kau yakin, Buta? Bagaimana jika kebebasan itu berubah menjadi jeruji baru? Ketika setiap orang berbicara hanya untuk dirinya sendiri, maka siapa yang layak untuk kita dengar? Jika semua pandangan dianggap benar, maka suara orang bijak dan jeritan orang gila akan bernilai sama, Buta. Pada akhirnya, yang akan menang hanyalah suara yang paling keras, atau yang paling indah. Dan bukankah hal itu sama saja dengan bunuh diri massal, karena kebenaran hanya akan ditentukan oleh gema, bukan makna?”
Si Buta terdiam. Ia termenung lama.
“Kau benar, Buntung. Di lembah tadi setiap orang hidup di dalam goa yang mereka ciptakan sendiri. Mereka berbicara pada dinding, berteriak kepadanya lalu terpesona oleh gema suaranya sendiri.”
Ia menunduk lebih dalam.
“Kebenaran yang lahir tanpa diuji hanyalah suara kosong yang memantul di dinding, dinding kesendirian. Ia hadir di dunia, tapi tak memberi makna bagi dunia. Dengan begitu yang tersisa hanyalah persaingan, antara yang lebih keras, lebih indah, atau malah yang lebih pandai meniru gema.”
Buntung memandangi sumber mata air yang semakin memantulkan cahaya indah keemasan dari matahari di waktu senja.
“Barangkali, Buta, di sinilah manusia belajar: bahwa kebebasan tanpa arah bisa sama sunyinya dengan kepatuhan tanpa tanya.”
Refleksi: Paradoks kebebasan
Di Lembah Suara, setiap orang memiliki kebebasannya sendiri-sendiri. Layaknya potret manusia masa kini yang sibuk berbicara, berteriak, bernyanyi, bahkan berdoa bukan dari dalam goa, tapi melalui gadgetnya masing-masing. Tidak ada otoritas yang mengikat, tidak ada satu kebenaran yang wajib diikuti Satu-satunya yang diatur dan dijamin di sini adalah adalah kebebasan untuk berbicara itu sendiri.
Saya kira begitulah wajah dunia kita hari ini. Setelah merasa lelah karena hidup di bawah bayang-bayang “kebenaran tunggal” dengan segala belenggunya, manusia saat ini berbondong-bondong melarikan diri ke dunia kebebasan. Dunia yang di dalamnya orang-orang tidak ada lagi yang mau tunduk pada otoritas: tidak pada agama, negara, bahkan pada nalar itu sendiri. Di sana semua orang merasa berhak untuk mendefinisikan hidupnya sendiri, hidup untuk dirinya sendiri dan sesuai dengan versinya sendiri. Sebuah era di mana Nietszche berkata “Tuhan telah mati”, sebuah metafora yang dia cetuskan yang bukan karena Ia benar-benar tiada, melainkan karena manusia telah berhenti mencari-Nya, manusia lebih sibuk menciptakan dirinya sendiri sebagai tuhan kecil dalam ruang yang sempit bernama kebebasan.
Dalam cerita di atas saya menggunakan alegori Goa untuk menggambarkan identitas manusia itu sendiri. Identitas yang dibangun oleh setiap orang dengan gelar, opini, ideologi, atau sekedar mempercantik halaman media sosial. Dengan berbekal identitas yang dia punya itu, dia kemudian coba untuk berteriak sekeras mungkin agar dunia tahu dia ada. Dunia seolah panggung untuk dirinya semata. Dunia harus tau itu, dunia harus mengakui kalo dia ada, dia adalah orang penting.
Namun alih-alih ditanggapi oleh orang lain, dia hanya mendengar gema dari apa yang dia teriakan sendiri. Padahal gema bukanlah makna—ia hanya suara yang berputar di ruang sempit, kehilangan konteks, kehilangan arah dan kehilangan tujuan.
Di era ketika semua orang berbicara, dan kebenaran tergantung pada sudut pandang manusianya. Ketika setiap pendapat dianggap benar, maka kita selayaknya bertanya, apakah kebenaran itu sendiri masih punya makna? Karena ketika semua orang punya versi kebenaran maka suara seorang professor akan sama nyaringnya dengan suara seorang ODGJ. Lantas untuk apa manusia mencari kebenaran jika kebenaran itu sendiri merupakan presepsi kita sendiri?
Mungkin jika Socrates hidup di masa kini dia akan bingung. Dia mungkin berpikir “Hidup macam apa yang dijalani oleh manusia-manusia ini, kehidupan yang kosong dan tak layak dijalani karena ia tak pernah diuji.”
Ya begitulah, kita hidup di zaman di mana kebenaran tak lagi diukur dari kedalaman, melainkan dari gaungnya yang paling keras. Yang viral dianggap benar, yang populer dianggap penting, yang diam dianggap kalah. Apakah mereka lupa, bahwa gema bukanlah makna ia hanya suara yang berputar di ruang sempit, kehilangan konteks, kehilangan arah dan kehilangan tujuan.
Akhirnya, kehidupan seperti ini pun memunculkan permasalahan lainnya. Di titik dimana manusia bisa hidup sesuai dengan versinya, justru di situ pula manusia kehilangan makna dalam hidupnya. Mungkin karena itulah belakangan muncul kegelisahan baru yang menghinggapi manusia, yakni kegelisahan eksistensial. Karena kebebasan itu sendiri manusia kemudian mulai bertanya, Apakah ini kebebasan atau sekedar keterasingan? Ini kemerdekaan atau kesepian? Ini kebebasaan atau kehampaan? Apa makna hidup? Apa tujuan hidup? Untuk apa aku diciptakan? Semua berenang di kepala manusia setiap harinya.
Inilah paradoks manusia modern: ia haus kebebasan, tapi takut kesunyian. Ia ingin menentukan dirinya sendiri, tapi tak kuasa menanggung konsekuensinya. Maka ia berteriak sekeras mungkin, bukan untuk dimengerti melainkan agar gema suaranya membenarkan keberadaannya. Karena tak ada yang akan mendengar sehingga yang kembali kepadanya bukanlah tanggapan dari orang lain, Tapi sekedar gema yang memantul pada dirinya sendiri.
Mungkin karena ini pula seorang Erich Fromm ingin lari dari kebebasan, atau mungkin ini juga yang membuat seorang Jean Paulo-Sarte bilang bahwa kebebasan adalah sebuah kutukan untuk manusia itu sendiri.
Ingat kawan. Setiap pilihan yang kita buat, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Misal anda berpikir tidak mau bersaing dengan orang lain dalam segala hal, boleh. Silahkan. Cuma ya resikonya adalah anda tidak mungkin bisa terbentuk seperti orang lain. Anda mungkin tidak akan punya pengalaman seperti orang lain. Anda ingin hidup bahagia, dengan foya-foya, pacaran, hidup bebas. Is okey silahkan, Cuma anda juga harus siap, karena dengan begitu. Artinya anda juga harus siap kehilangan banyak waktu untuk belajar dan berproses untuk menjadi manusia seutuhnya. Anda gamau sholat, gamau ibadah, isokey, terserah. Silahkan, yang penting anda siap menerima konsekuensi hidup tanpa arah yang akan segera menimpa hidupmu.
Ingat hidup bukan hanya memilih apa yang kita suka, tapi juga mengukur dan mengira konsekuensi yang akan kita terima di masa depan.
Mungkin, di sinilah Si Buta dan Si Buntung mulai belajar:
Bahwa manusia tidak bisa hidup hanya dari kepastian, tapi juga tidak bisa hidup hanya dari kebebasan.
Eksistensialisme mengajarkan bahwa kebenaran tidak pernah datang dari luar, tidak pula bisa diwariskan sebagai doktrin. Ia lahir dari perjumpaan manusia dengan dirinya sendiri dari kesadaran bahwa hidup adalah pilihan yang harus ditanggung sepenuhnya.
Ingat!!!, kebebasan yang sejati bukanlah kebebasan untuk berteriak tanpa arah, melainkan keberanian untuk menanggung konsekuensi dari setiap pilihan yang kita buat sendiri.
Penulis: Muhammad Ali Magfur – Mahasiswa International Islamic University Malaysia – Pengurus Pusat KMNU Nasional