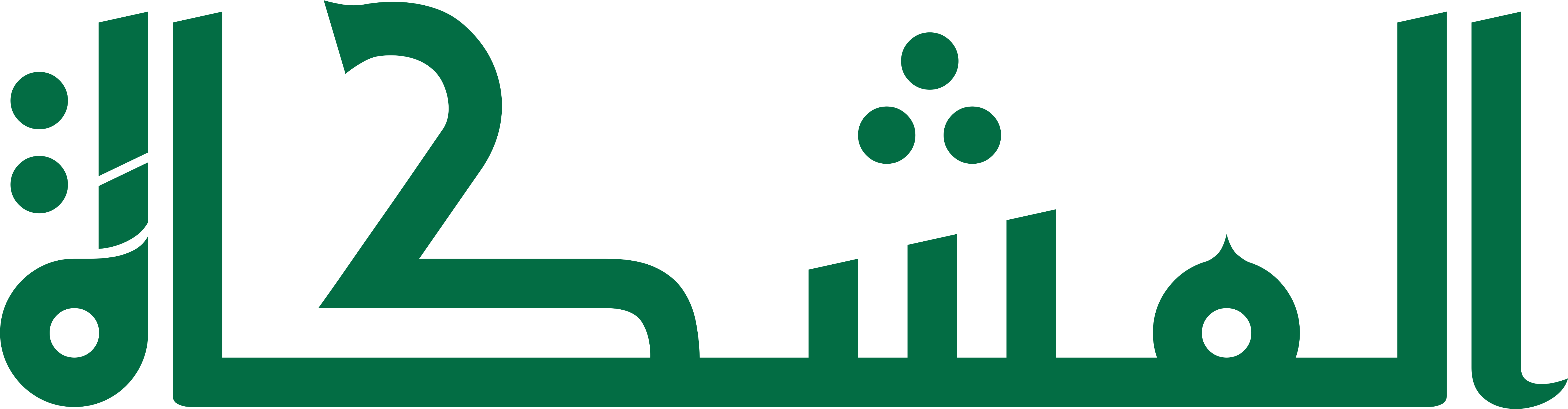Kebenaran mutlak ala desa batu
Setelah puas bermain dan meneguk air dari sumber mata air itu, si Buta dan si Buntung duduk di atas sebuah batu besar di tepi aliran yang jernih. Angin gunung berhembus pelan, membawa aroma lumut dan tanah basah.
Si Buntung menoleh, berbisik pelan,
“Apa yang kau rasakan setelah sampai di sini, Buta?”
Si Buta tersenyum samar.
“Entahlah buntung… bagiku, air di sini tak ada bedanya dengan air di belakang rumahku.”
Buntung mengangguk pelan.
“Kau benar buta. Aku pun melihat hal yang sama. Air di hadapan kita ini tak berbeda dengan air di tempat kita biasa bermain.”
Si Buta terdiam sejenak, lalu bertanya ragu,
“Apakah kita salah tempat, Buntung? Kau yakin ini sumber air kehidupan sejati?”
“Aku yakin, buta” jawab Buntung sambil membuka lipatan peta kusut di tangannya.
“Kita sudah melewati semua desa yang ditunjukkan di peta ini. Kau ingat desa pertama, Buta?”
“Maksudmu… desa tempat aku tersandung batu dan kita terguling bersama itu?” tanya Buta.
Buntung tertawa kecil.
“Benar sekali! Desa Batu. Tapi, anehnya, aku masih memikirkan kehidupan di sana.”
“Kenapa? “Aku hanya mendengar mereka berdoa bersama sama tadi, dan berdasarkan cerita dari beberapa warga di kampong kita, orang-orang di desa itu sudah menjalankan kehidupan seperti itu sejak lama buntung.” Setiap pagi mereka berkumpul di bawah batu besar, berdoa, dan mempersembahkan sebagian harta yang mereka punya. Mereka sudah melakukannya selama ratusan tahun — luar biasa, bukan? Tanya si buta”
Buntung menatap air yang beriak pelan. Kemudian berkata
“Entahlah buta, aku sendiri agak ngeri melihatnya. Tadi Aku melihat orang tua memaksa anak-anak mereka melakukan hal yang sama, bahkan wajah mereka banyak yang tampak kosong — seperti tak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Mereka tampak tak punya pilihan lain, selain mengikuti apa yang sudah ada dan diyakini bersama-sama di desa itu. Apa mungkin di sana, memang tak seorang pun berani berbeda. Mereka pakai baju yang sama, beribadah dengan cara yang sama dan di tempat yang sama juga. Apakah disana perbedaan dianggap satu hal yang salah ya buta?”
Si Buta menarik napas panjang.
“Ketaatan seperti itu memang tampak suci, tapi sebenarnya buta.
Mereka menolak perubahan karena takut menyalahi tradisi. Lihat saja, lututku masih berdarah karena tersandung batu di jalan mereka. Andaikan mereka mau berpikir sedikit saja, jalan itu tak akan seburuk itu.”
“Mungkin, kebenaran dianggap harga mati di sana; ia tak perlu dipikirkan, apalagi diperdebatkan. Sehingga Mereka hanya diajari untuk meyakini, tunduk, dan beramal — bukan untuk berpikir.”
Buntung terdiam, menatap air yang mengalir.
Dalam hati ia bergumam,
“Apakah benar kebenaran seperti yang diyakini orang-orang Desa Batu? Jika iya, bagaimana mereka bisa bertahan di dunia yang terus berubah?”
“Hoi, Buntung! Diam saja kau!” seru si Buta. “Orang lagi ngomong malah bengong. Kau tidur, ya?”
Buntung tersentak, lalu tertawa.
“Hehe, maaf Buta. Aku terlalu menikmati pemandangan ini.”
“Ish, kau ini!” sahut Buta sambil pura-pura mengayunkan tangan untuk memukul, padahal ia sendiri tak tahu persis di mana Buntung duduk.
Mereka tertawa kecil bersama, sebelum kembali diam.
Keheningan sore turun perlahan di sekitar mata air — seolah gunung itu sendiri sedang berpikir.
Bersambung…
Nantikan petualangan si buta dan si buntung di desa-desa selanjutnya, !
Ketika Kebenaran Menjadi Batu
Di dunia ini, ada sebagian manusia yang percaya bahwa kebenaran itu hanya satu, ia utuh, suci, tak bercela seperti batu yang keras, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Pandangan kebenaran semacam itu memang memberi rasa aman dan kepastian. Kita hanya harus tunduk dan patuh tanpa perlu menyoal berpikir ulang. Dalam dunia yang penuh dengan kekacauan, keyakinan bahwa “ada satu kebenaran tunggal” tampak seperti jangkar yang menahan manusia agar tak terombang-ambing.
Namun, jangkar yang sama juga bisa juga seringkali malah menjadi beban. Sebuah beban yang menahan kita dari kemungkinan untuk bergerak, menengok, bahkan untuk bertanya apalagi berinovasi.
Pola pandangan seperti ini biasanya disebut dengan paradigma esensialis, Sebuah cara berpiki yang selalu memikat karena menjanjikan kepastian. Ini halal, ini haram, ini ilmiah, dan yang lainnya. Orang dengan paradigm seperti ini berpandangan bahwa segala sesuatu memiliki hakikat yang menentukan segalanya: baik dan buruk, benar dan salah, suci dan najis.
Tentu bukan hanya tentang agama, orang-orang modern pun melakukan hal yang sama Cuma mereka beda Tuhan saja. Ada menyembah ideologi, sains, filsafat, modernitas, atau bahkan menyembah dirinya sendiri. Mungkin mereka berbeda-beda tapi polanya sama yakni ada keyakinan bahwa di dunia ini ada satu hakikat tunggal yang harus dijadikan ukuran bagi semua.
Ambil contoh yang belakangan rame, ada yang bilang “Kalo mau maju harus menjunjung kesetaraan bagi semua manusia, ketaatan mutlak kepada guru adalah bentuk feodalisme dan mengambat kemajuan.” Kedengarannya rasional bukan, tapi benarkah ia berlaku universal?
Andaikata pra-syarat kemajuan adalah dengan kesetaraan lantas bagaimana mereka menjelaskan konflik yang banyak terjadi di timur tengah yang terjadi gara-gara mereka dipaksa untuk hidup dalam sistem demokrasi yang menjunjung kesetaraan? Atau bagaimana dengan guru-guru di Indonesia yang kehilangan kewibawaan di mata murid mereka karena semua dianggap “setara”?
Pola seperti ini membuat kebenaran tidak lagi tumbuh dari hidup, melainkan hidup yang dipaksa tunduk kepada sesuatu yang dianggap benar. Dalam paradigma ini, kesalahan terbesar manusia bukanlah dosa atau kebodohan, tetapi karena mereka berbeda.
Di sinilah letak ironi esensialisme: atas nama kebenaran, ia menutup mata terhadap kenyataan bahwa manusia tidak pernah tunggal. Bahwa hidup bukan rangkaian hukum yang pasti, melainkan ruang tak menentu yang terus berubah oleh waktu, tubuh, dan makna.
Ketika kita meyakini hanya ada satu kebenaran, kita kehilangan kepekaan terhadap kenyataan paling sederhana: bahwa manusia hidup dalam penafsiran, bukan dalam kepastian.
Kebenaran tidak turun seperti hujan dari langit, ia lahir dari pergulatan manusia dengan dirinya sendiri dan dengan dunia yang tak pernah selesai ia pahami.
Barangkali di titik ini, kita perlu bertanya ulang: apakah kebenaran itu sesuatu yang ditemukan, atau sesuatu yang kita ciptakan melalui keberadaan kita sendiri? Pertanyaan ini bukan sekadar permainan kata, melainkan cara untuk menyelamatkan kemanusiaan kita dari dogma yang keras seperti batu. Karena selama kebenaran masih dipahami sebagai sesuatu yang berada di luar manusia—sesuatu yang sudah lengkap dan tinggal diterima—maka manusia akan terus kehilangan dirinya di bawah bayang-bayangnya sendiri.
Saya tidak sedang menolak kebenaran, tetapi menolak tirani akan kebenaran,yakni saat kebenaran berhenti menjadi jalan pencarian, dan berubah menjadi alat untuk menundukkan.
Kita butuh cara baru untuk berhubungan dengan kebenaran: bukan dengan tunduk, tetapi dengan berdialog. Bukan dengan mencari kepastian, tetapi dengan menanggung ketidakpastian secara sadar.
Dari sinilah pintu menuju eksistensialisme terbuka: bahwa kebenaran bukan lagi sesuatu yang menunggu untuk ditemukan, tetapi sesuatu yang tumbuh bersama keberadaan manusia itu sendiri. Bahwa menjadi benar bukan berarti menemukan hakikat yang tunggal, melainkan berani hidup sepenuhnya dalam ketegangan antara keyakinan dan keraguan. Dan mungkin, di antara ketidakpastian itulah, manusia untuk pertama kalinya benar-benar hidup.
Nantikan kisah si buta dan si buntung selanjutnya, dan kita akan sama-sama bermain ke dunia eksistensialisme, di mana kebenaran hanya bisa ditemukan dari dalam manusia itu sendiri.
Penulis: Muhammad Ali Magfur – Mahasiswa International Islamic University Malaysia – Pengurus Pusat KMNU Nasional