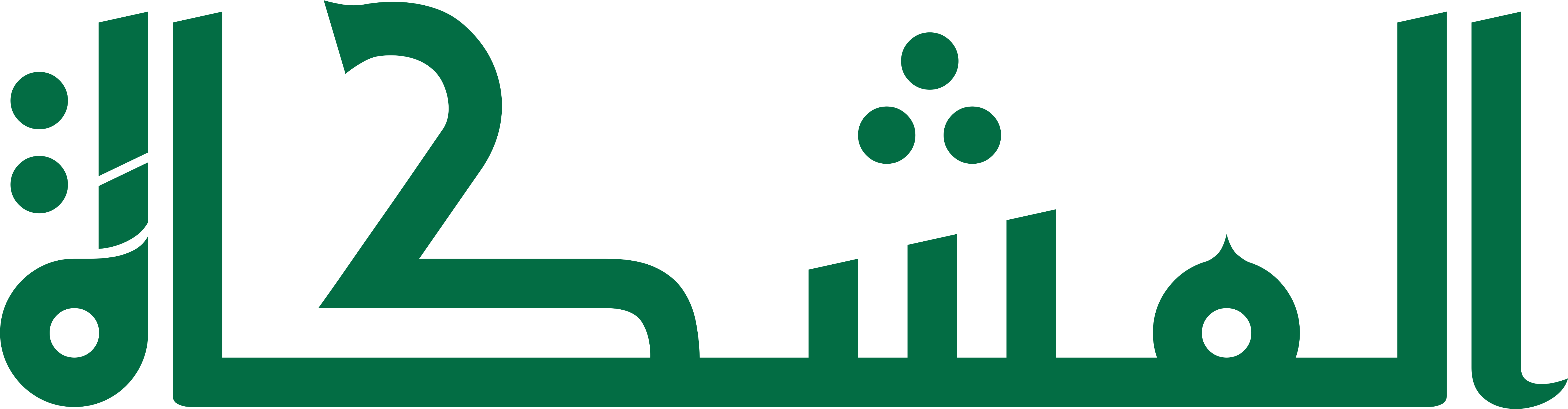Agama Islam yang merupakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad memiliki misi untuk menegakkan keadilan dan membela kaum tertindas. Islam mengajarkan nilai-nilai kesetaraan, saling menghargai, dan saling membantu satu sama lain. Islam menolak segala bentuk ketidakadilan, hegemoni, termasuk juga ketidaksetaraan gender. Pada zaman Nabi Muhammad kaum perempuan menempati posisi yang cukup baik, memperoleh hak yang lebih besar dibandingkan dengan zaman jahiliyah. Perempuan bisa memperolah warisan, memiliki hak milik sendiri, berhak menentukan dirinya sendiri, poligami yang pada mulanya tidak terbatas menjadi dilimitasi maksimal 4 istri dengan persyaratan yang ketat. Nabi juga secara bertahap mengubah sistem tradisi masyarakat Arab yang buruk, seperti larangan mengubur anak perempuan hidup-hidup karena rasa malu.
Sekalipun pada masa Nabi perempuan memperoleh derajat yang lebih tinggi, namun paska Nabi wafat, pada masa kekhilafan Umar Bin Khattab, kehidupan perempuan sempat dilimitasi, seperti perempuan hendaknya tetap di rumah dan tidak ke masjid, dan lain-lain. Sampai saat ini Islam mendapat sorotan berbagai pihak karena memiliki norma agama yang terkesan bias gender. Bahkan di berbagai negara Islam, kaum perempuan tidak memiliki akses, kebebasan sebagaimana laki-laki, perempuan hanya mengurusi urusan dapur dan mencuci, tidak boleh bekerja di ruang publik, dan berbagai tradisi yang mengekang terhadap perempuan.
Salah satu aspek penting dalam mewujudkan keadilan gender (gender of justice) adalah menegaskan kembali tafsir agama, perlu evaluasi dan reinterpretation guna mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, termasuk kepentingan perempuan dalam kaitannya dengan relasi gender, sehingga pemikiran keagamaan tidak lagi menjadi penghambat proses gender equality.

Konsep Gender
Gender terbentuk melalui proses yang cukup panjang dan disebabkan oleh beberapa faktor seperti dibentuk, dikonstruksikan secara sosial dan kultural, melalui negara bahkan juga ajaran agama. Hal ini didasarkan atas Q.S al-Hujurat: 13.
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْاۚ
“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.”
Kutipan ayat tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan dua diksi secara terpisah (khalaqa & ja’ala). Sekalipun makna keduanya itu muradif (membentuk, mewujudkan, menjadikan), tetapi makna khalaqa lebih mengarah pada pembentukan, penciptaan secara murni tanpa campur tangan pihak lain, sedangkan ja’ala memungkinkan campur tangan dan faktor eksternal untuk menjadikan/mewujudkan perkara tersebut.
Dengan demikian, bisa dipahami bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial, ekonomi, nilai, budaya, serta faktor-faktor non-biologis yang berkembang dalam suatu masyarakat. Gender terbentuk melalui proses yang panjang dan disebabkan oleh beberapa faktor misalnya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dan dikonstruksikan secara sosial dan kultural melalui negara dan juga ajaran agama.
Gender menjadi isu karena adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang, seperti subordinasi, marginalisasi, perempuan dilekati dengan stigma sebagai orang yang tidak memiliki kapabilitas dalam bekerja di ranah publik, sehingga hanya cocok ditempatkan dalam ranah domestik. Selain itu, perempuan sebagai istri acapkali dijadikan objek kekerasan fisik, mental, dan tindakan lainnya. Tidak sedikit laki-laki yang merendahkan, memperlakukan tak adil terhadap perempuan atas dasar legitimasi agama.
Sebagian individu maupun kelompok dalam masyarakat memahami bahwa perempuan tidak memiliki kapabilitas yang sama dengan laki-laki, perempuan harus dibelakang menjadi makmum, dan perempuan sebagai istri dianggap hanya mampu mengurusi dapur dan tugas mencuci. Persepsi demikian didasarkan atas kutipan ayat, misalnya:
ٍاَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْض
“Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan”.
Berdasarkan ayat tersebut, mereka meyakini bahwa laki-laki memang ditakdirkan sebagai pemimpin, hanya laki-laki yang memiliki kapasitas dan kesanggupan di berbagai ranah. Selain itu, laki-laki juga berpandangan bahwa mereka memiliki hak yang lebih daripada perempuan, argumen ini didasarkan atas ayat mengenai poligami.
فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَۚ
“Nikahilah olehmu perempuan yang kamu senangi dua, tiga, maupun empat”. Dengan demikian, laki-laki berhak menikah lebih dari satu istri, sedangkan perempuan tidak boleh melakukan poliandri.
Menurut Ashgar Ali, dalam menginterpretasikan Al-Qur’an setidaknya mencakup 3 elemen pokok. Pertama, membedakan ayat-ayat yang memiliki aspek normatif dan kontekstual sehingga menempatkan ayat yang bersifat kulliyat sebagai ayat yang dapat melintasi ruang dan waktu. Selain itu, penting juga untuk memahami sesuatu yang diinginkan oleh Allah dan sesuatu yang dibentuk oleh fakta empiris pada waktu ayat itu diturunkan. Kedua, penafsiran terhadap Al-Qur’an sangat tergantung pada kondisi, sosio-kultural yang melatarbelakangi para mufassir, sehingga perlu dipertimbangkan produk pemikiran yang dihasilkan. Ketiga, makna ayat terbentang oleh waktu sehingga penafsiran klasik memiliki perbedaan dibandingkan dengan penafsiran kontemporer. Apabila pembacaan terhadap teks-teks agama dilakukan secara dangkal, tekstual, dan harfiah, maka akan menghasilkan konklusi yang konservatif, serta tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Ayat-ayat yang seolah-olah terkesan bias gender tidak bisa dipahami apa adanya dan sembarangan.

Keadilan sebagai Pilar
Salah satu prinsip dalam ajaran Islam adalah persamaan (al-musawa, equality). Persamaan antar manusia merupakan prinsip universal yang merupakan basis, prinsip fundamental agama, dan prinsip ini tidak bisa dinafikan oleh ayat-ayat juz’iyat (particular). Kesetaraan dan keadilan adalah pilar utama bagi tegaknya kehidupan umat manusia. Pada dasarnya, ajaran Islam baik Al-Qur’an maupun hadits mengandung berbagai prinsip kesetaraan (equality, al-musawa), keadilan sosial (social justice, al-‘adl al-ijtima’i) dan menolak berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan. Prinsip ini tidak hanya termaktub dalam Al-Qur’an dan hadist, tetapi juga dideklarasikan oleh Nabi Muhammad ketika di Madinah. Peristiwa ini dikenal dengan shahifah Madinah (piagam Madinah). Dalam Pasal 1 Ayat (1) Piagam Madinah menyebutkan “Manusia adalah satu keluarga, sebagai hamba Allah dan berasal dari Adam. Semua orang adalah sama dipandang dari martabat dasar manusia dan kewajiban dasar mereka tanpa diskriminasi ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, kepercayaan agama, status, atau pertimbangan lain. Keyakinan yang benar menjamin berkembangnya penghormatan terhadap martabat manusia ini.”
Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang memiliki persamaan status (Q.S al-Hujurat: 13), persamaan terhadap penilaian amal perbuatan (Q.S an-Nahl: 97, Q.S al-Ghafir: 40, dan Q.S an-Nisa’: 124). Persamaan tugas (Q.S an-Naml: 62, Q.S al-An’am: 165). Persamaan sebagai hamba Allah (Q.S az-Dzariyat: 56). Dengan berbagai prinsip kesetaraan tersebut, menunjukkan bahwa Islam menghendaki adanya kesetaraan gender (gender equality). Ayat-ayat tersebut menurut Husein Muhammad merupakan ayat yang universal, yaitu ayat tauhid yang makkiyah, serta bersifat kokoh (muhkamah). Ayat yang demikian tidak bisa di-nasakh oleh ayat-ayat juz’iyat.
Adanya teks agama yang terkesan bias gender seperti “laki laki itu adalah pemimpin bagi perempuan”, ayat tersebut pada dasarnya tidak mengharuskan laki-laki menjadi pemimpin di berbagai ranah dan juga tidak mengandung unsur normatif, tetapi bersifat relatif. Sehingga tidak bisa dimaknai secara mutlak, universal. Sedangkan ayat poligami, harus dipahami secara sosial-historis budaya Arab pada saat itu. Sehingga poligami bukan ditujukan bagi laki-laki secara umum. Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini tidak menganjurkan laki-laki untuk melakukan poligami, bahkan kebolehannya merupakan pintu kecil disertai syarat yang cukup ketat. Sebelum Islam datang, praktik poligami sudah mengakar dalam budaya Arab, sehingga Al-Qur’an merespons praktik tersebut dan melimitasi maksimal 4 istri.
Dari pemaparan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang dianggap misoginis merupakan hal yang absah, bahkan merupakan suatu keniscayaan. Dalam memahami nash (Al-Qur’an dan Hadist) diperlukan berbagai kerangka keilmuan agar bisa menembus inti sari dari kandungan nash tersebut, seperti sabab an-nuzul, nasikh-mansukh, makiyah-madaniyah, muhkamah-mutasyabihah, ‘am-khass, haqiqi-majazi, muthlaqah-muqayyadah, dan lain-lain.
Penulis: Alfaenawan, Santri 8 KMNU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Editor : Fazlur Rahman, Santri 7 KMNU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.