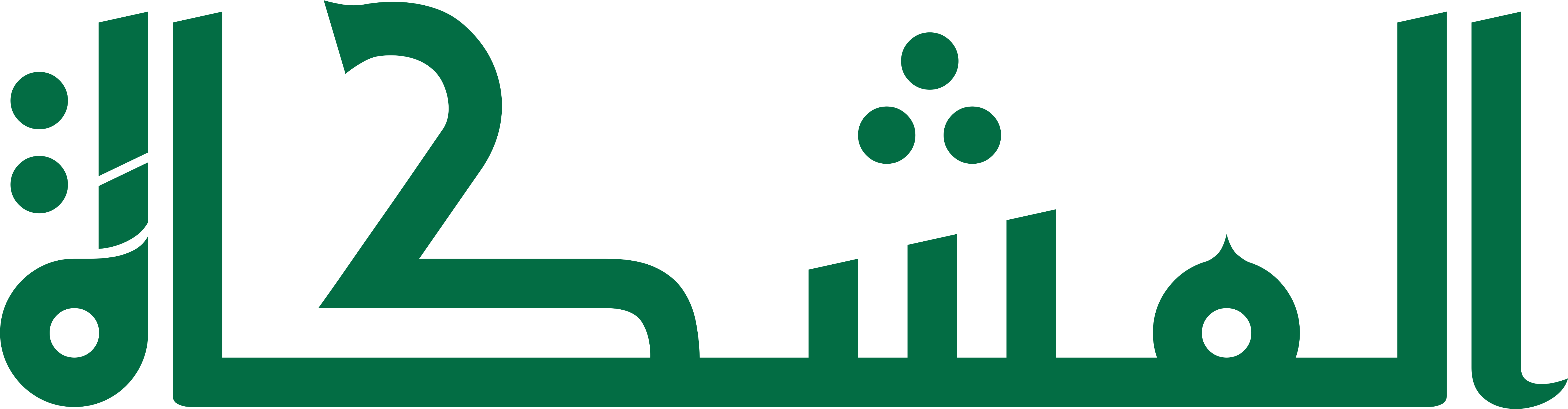Hari ini kita sering mendengar ajakan untuk kembali pada agama yang “murni.” Di jalan-jalan, ada spanduk yang menyerukan umat agar beribadah sesuai “ajaran asli.” Di media sosial, semakin banyak akun yang mengkampanyekan Islam versi “tanpa campuran budaya,” seolah-olah hanya itulah cara beragama yang benar. Bahkan, tidak jarang ajakan ini disertai sindiran, cibiran, atau vonis sesat kepada praktik keagamaan yang dianggap tercampur dengan tradisi lokal.
Sekilas, ajakan itu terdengar mulia: siapa yang tidak ingin beragama secara benar dan murni? Namun kalau kita mau jujur, cita-cita itu mustahil tercapai. Tidak ada satu pun umat beragama di dunia ini yang benar-benar menjalankan agamanya secara steril dari pengaruh manusia. Setiap praktik keberagamaan—dari cara berpakaian, cara berdoa, hingga bagaimana kita merayakan hari besar—selalu lahir dari proses panjang: ditafsirkan, diperdebatkan, lalu disepakati dalam masyarakat. Dengan kata lain, agama yang kita jalani hari ini bukan hanya hasil wahyu, tetapi juga hasil konstruksi sosial.
Pernahkah Anda berpikir, apakah semua yang kita lakukan sebagai umat beragama benar-benar ajaran murni dari wahyu, atau sebenarnya hasil dari perdebatan panjang dalam masyarakat? Pertanyaan ini sering membuat orang tidak nyaman. Tapi justru dari situ kita bisa melihat sisi menariknya.
Tahun 1966, Peter L. Berger dan Thomas Luckmann mengemukakan teori yang sederhana tapi mengguncang: realitas sosial itu tidak datang begitu saja dari langit, melainkan dibangun oleh manusia melalui interaksi yang berulang. Dengan kata lain, banyak hal yang kita anggap “ajaran tetap” bisa jadi lahir dari konstruksi sosial.
Mari kita uji lewat contoh yang sering jadi kontroversi.
Pertama, hijab. Banyak orang di Indonesia yakin hijab adalah kewajiban mutlak bagi semua perempuan Muslim. Tapi, tahukah Anda bahwa tidak semua ulama sepakat? Ada yang mengatakan hijab adalah keharusan, ada pula yang berpendapat menutup aurat tidak harus dengan bentuk hijab seperti yang kita kenal sekarang. Lagi pula, gaya berpakaian Muslimah berbeda-beda di setiap negara: di Iran ada chador, di Arab Saudi ada abaya dan niqab, di Indonesia populer dengan kerudung segi empat, sementara di beberapa wilayah Afrika perempuan Muslim justru memakai kain berwarna-warni. Kalau benar ajarannya tunggal dan baku, kenapa wujudnya bisa begitu beragam—dan bahkan diperdebatkan tingkat kewajibannya?
Kedua, ucapan Natal. Sebagian Muslim menolak mentah-mentah mengucapkan selamat Natal dengan alasan itu berarti mengakui keyakinan orang lain. Tapi banyak ulama lain membolehkan, dengan dasar hidup berdampingan dan menjaga harmoni sosial. Jadi, satu tindakan kecil—sekadar ucapan “Selamat Natal”—ternyata bisa dipandang haram oleh satu kelompok, dan dianggap wajar oleh kelompok lain. Bukankah ini menunjukkan bahwa yang kita anggap “hukum agama” juga lahir dari tafsir dan kesepakatan sosial, bukan sesuatu yang seragam sejak awal?
Ketiga, poligami. Sebagian kelompok memperjuangkannya sebagai sunnah yang murni. Tapi kenyataannya, praktik poligami sangat berbeda tergantung konteks sosial. Di Tunisia, poligami dilarang. Di Indonesia, poligami diatur ketat lewat undang-undang. Sementara di Arab Saudi, ia lebih longgar. Kalau memang “aturan murni agama” itu satu dan sama, kenapa praktiknya bisa begitu berbeda?
Contoh-contoh ini mengingatkan kita pada pesan Berger dan Luckmann: realitas sosial selalu dibangun, diperdebatkan, dan kemudian disepakati bersama. Apa yang hari ini dianggap “ajaran wajib” bisa jadi dulu adalah hasil perdebatan panjang di kalangan ulama maupun masyarakat.
Maka, pertanyaan yang layak kita ajukan adalah:
Apakah kita berani mengakui bahwa cara kita beragama tidak sepenuhnya “turun dari langit,” melainkan juga hasil dari budaya, politik, dan tafsir manusia?
Kalau kita berani jujur, mungkin kita akan lebih bijak dalam menghadapi perbedaan. Kita tidak lagi mudah menuduh orang lain salah, karena kita sadar: agama yang kita jalani bukan hanya teks, tapi juga konstruksi sosial yang selalu hidup dan berubah.
Pada akhirnya, keyakinan kita memang bersumber dari teks suci, tetapi cara kita menjalaninya selalu bersentuhan dengan budaya, tafsir, bahkan politik. Itulah mengapa mustahil ada bentuk keberagamaan yang benar-benar “murni”, steril dari pengaruh manusia.
Setiap jilbab yang dipakai, setiap doa yang diucapkan, bahkan setiap ucapan “Selamat Natal” atau penolakannya, semuanya melewati proses panjang: ditafsirkan, diperdebatkan, lalu diwariskan oleh masyarakat. Jadi, beragama tanpa campur tangan manusia hanyalah ilusi.
Justru di situlah letak keindahannya: agama bukan benda mati yang membeku di langit, melainkan sesuatu yang hidup di bumi—dibentuk oleh manusia, dijalani bersama, dan terus menyesuaikan diri dengan zaman.
Maka pertanyaannya bukan lagi “apakah kita beragama dengan murni atau tidak”, melainkan: bagaimana kita memastikan bahwa konstruksi sosial yang kita bangun lewat agama melahirkan kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan.
Penulis: Muhammad Ali Magfur, S.H – Mahasiswa International Islamic University Malaysia